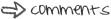Mereka
Pagi yang seperti biasa. Membosankan. Semua rutinitas yang terus berulang membuatku tak ubahnya seperti robot dalam menjalani hidup ini. Pagi yang sama, kegiatan yang sama, halte yang sama pemandangan yang sama. Namun ada satu hal yang selalu menarik perhatianku setiap pagi, yaitu sepasang kakek-nenek yang berada di seberang halte tempat aku biasa menunggu bus.
Hanya sepasang manula yang sudah tua renta. Kurasa mereka gelandangan, setiap pagi aku selalu melihat mereka di pinggir jalan dengan pakaian yang kumal dan compang-camping yang sama. Sebuah gerobak reyot selalu setia mendampingi mereka, gerobak yang biasa digunakan sang kakek untuk membawa istrinya jalan-jalan. Tidak ada yang istimewa dari penampilan mereka. Namun yang menarik perhatianku adalah rasa di antara mereka. Ada rasa sayang yang sangat jelas terpancar dari mata si kakek saat memandang istrinya yang bahkan sudah sulit berbicara. Stroke kurasa. Setiap pagi aku melihat kakek itu akan menyuapi si nenek dengan sabar dan penuh kasih sayang, mengajaknya bicara walaupun tak lagi mendapat tanggapan yang jelas, hanya anggukan lemah dan senyum yang terlihat aneh, bahkan kadang menyeramkan menurutku. Namun demikian. Namun demikian, tak pernah aku melihat kakek itu makan. Hanya segelas-dua gelas air mineral. Itu saja. Terkadang pula aku melihat mereka tidur di trotoar di seberang jalan tersebut. Lebih tepatnya, sang nenek tertidur dengan pulas, sedangkan sang kakek berbaring di sebelahnya, menyelimutinya dengan kain tipis yang sudah kumal dan lusuh. Membelai rambut sang nenek yang sudah memutih dan kusut—entah kapan terakhir kali rambut itu dicuci—serta memandang wajah tidur sang nenek dengan penuh cinta. Terkadang aku merasa iri melihat sang nenek, betapa bahagia hidupnya karena ada yang mencintainya seperti itu. Memang, mungkin mereka tidak memiliki rumah atau harta, tapi seperti yang temanku pernah katakan, mungkin cinta memang sudah cukup.
Bus menuju sekolahku datang. Sudah waktunya aku pergi. Selamat tinggal kakek, selamat tinggal nenek, selamat datang kenyataan. Sekali lagi, rutinitas berulang kembali.
Pagi yang sama, rutinitas yang sama. Sudah lama aku merasa bosan dengan hidupku. Terkadang aku berpikir untuk mengakhiri hidup saja. Toh hidupku seakan tidak bertujuan ini, untuk apa aku terus melanjutkan hidup? Haha! Mengerikan, pikiran untuk mengakhiri hidup saja sudah membuatku merinding! Ya sudahlah, terlalu banyak mengeluh juga tidak akan mengubah kenyataan bahwa rutinitas ini akan terus berulang. Terkadang aku menantikan sebuah drama dalam hidupku, agar segalanya menjadi lebih menarik. Entahlah, mungkin sebuah drama yang menyedihkan? Atau mengharukan? Apapun boleh asalkan hidupku menjadi menarik.
Seperti biasa, aku memandangi pasangan unik di seberang jalan. Namun hari ini ada yang berbeda. Sang kakek tetap membelai rambut istrinya dengan lembut dan penuh kasih sayang, bahkan sekali-dua kali mengecup keningnya dengan mesra, tetapi aku tidak melihat adanya reaksi dari sang nenek. Sepertinya sang nenek hanya diam, terkulai lemas dalam gerobak tempatnya biasa tidur.
Rasa penasaran yang besar mendorongku untuk menyebrangin jalan yang agak senggang pagi itu. Perlahan aku menghampiri sang kakek yang masih tersenyum memandangi istrinya dengan penuh cinta. “Maaf, Kek,” sapaku ragu-ragu, “ada apa dengan nenek?” Sang kakek hanya tersenyum lembut mendengar pertanyaanku yang polos. Sorot matanya—aku tidak tahu, terlalu banyak emosi bercampur-aduk di sana—terlihat sendu, rasa cinta, sedih, pilu, sakit, seakan itu semua menari-nari dalam matanya yang bening dan terlihat lelah. Kantung matanya yang gelap seolah semakin memancarkan rasa pilunya. Baru kali ini aku melihatnya sedekat ini.
“Adik kelas berapa?” Tanyanya lembut, seolah menghindar untuk menjawab pertanyaanku tadi. Aku hanya menatapnya bingung, tidak mengerti korelasi antara pertanyaan yang kuajukan tadi dengan pertanyaan yang diajukannya.
“Umm, kelas 3 SMP, Kek,” jawabku pada akhirnya. Senyum di wajah kakek itu semakin mengembang, mempertegas kerut-kerut di wajahnya yang sudah terlihat uzur.
“Adik mau berangkat sekolah?” Tanyanya lagi, memandang seragam putih-biruku. Aku menimbang-nimbang, sebentar lagi aku akan menghadapi ujian nasional, tetapi perasaanku mengatakan bahwa lebih baik untuk hari ini aku duduk dan menemani sang kakek dan nenek. Akhirnya perlahan menggelengkan kepala. “Mau menemani kakek di sini? Ada sebuah dongeng yang ingin kakek ceritakan,” ujarnya sambil menepuk-nepuk trotoar, menyuruhku untuk duduk di sebelahnya. Dalam hati aku bertanya-tanya, apakah kakek ini benar dapat dipercaya? Dongeng macam apa yang ingin diceritakannya?
Kakek itu berdehem, mempersiapkan diri untuk memulai ceritanya. Tangannya yang sudah terlihat kisut, menggenggam tangan istrinya erat-erat, seolah takut istrinya akan menghilang bila ia melepaskan genggamannya tersebut. Kemudian dia memandang istrinya sekali lagi, sebelum akhirnya mengalihkan pandangannya pada diriku yang duduk menunggu. “Dulu sekali, ada pasangan suami-istri yang bahagia,” sang kakek memulai ceritanya, “mereka hidup bergelimang harta dengan anak-anak yang sehat, lucu, cerdas, tampan, dan cantik.”
“Namun, suatu hari, sang suami merasa tidak puas dengan kehidupannya. Di matanya, istrinya telah buruk rupa, sudah tua, sudah tidak menarik bagi birahi si lelaki ini. Dengan kurang ajar, lelaki tersebut kemudian meniduri sekretarisnya. Bukan memerkosa, tetapi sekretarisnya pun menawarkan diri. Tubuh yang putih mulus dan molek, rambut ikal yang menggoda, sungguh perempuan idaman setiap lelaki. Tidak terkecuali lelaki ini.
Berulang kali dia tidur dengan sekretarisnya tersebut. Sampai akhirnya berita ini menyebar di seluruh kantornya. Termasuk istri dan anak-anaknya pun mendengar hal ini. Sedih tak terkira sudah istrinya, tak luput pun anak-anaknya—bahkan mereka sudah penuh diliputi kemarahan tiada tara terhadap ayahnya. Namun lelaki ini tidak peduli. Baginya hartanya sudah cukup untuk membayar semua kesalahannya, baginya selama hartanya masih mengalir untuk keluarganya, itu sudah membuat keluarganya bahagia. Semua itu salah, istrinya sudah hancur-lebur hatinya, tetapi tetap bersikukuh untuk terus berada di sisi suaminya. Ia yakin suatu saat suaminya akan kembali ke jalan yang benar, dan ia bersedia untuk menunggu hingga saat itu tiba. Tanpa pengecualian, kondisi apa pun.
Lelaki ini semakin lama semakin terikat dengan sekretarisnya ini. Lama-kelamaan segala hartanya mulai diberikan kepada perempuan tersebut. Hal ini semakin memuncakkan kemarahan anak-anaknya. Sudah berulang-kali anak-anaknya berkata kepada ibunya untuk berpisah saja dengan lelaki ini, tetapi ibunya tetap bersikukuh, dia percaya bahwa cinta suatu saat dapat mengalahkan segalanya. Konyol, itulah pikir anak-anaknya pada saat itu. Harta mereka semakin lama semakin menipis. Bahkan ahli waris sudah dipindah-tangankan kepada sekretarisnya tersebut, tanpa mengacuhkan pendapat dari anak-anak maupun istrinya.
Anak-anaknya pada akhirnya merasa muak dengan segala tingkah-polah ayahnya. Mereka yang saat itu sudah beranjak dewasa, memutuskan untuk keluar dari rumah tersebut. Proses membujuk sang ibu gagal, sang ibu tetap dengan keras kepala mengatakan akan menunggu suaminya kembali. Akhirnya apa mau dikata, sang ibu pun ditinggalkan sendiri oleh anak-anaknya, sementara satu per satu perabotan dan benda-benda dalam rumah tersebut mulai lenyap karena digunakan lelaki tersebut untuk membiayai sekretarisnya.
Pada akhirnya, seperti yang sudah diduga, lelaki ini kehabisan semua hartanya. Dia pun jatuh miskin. Ditambah lagi, dengan kurang ajarnya sekretaris ‘teman bermainnya’ pun meninggalkannya, “sudah tidak ada harta yang bisa kuambil lagi darimu,” itulah kata-kata terakhir dari sekretarisnya sebelum pergi meninggalkannya. Lelaki ini pun sudah dipecat dari pekerjaannya karena skandal yang dimilikinya. Sudah tidak ada lagi harta yang dimilikinya. Hanya satu yang masih dimilikinya, cinta dari istrinya. Hanya itu yang tersisa.
Saat itulah kemudian lelaki ini menyadari, betapa berharganya istrinya. Bahwa istrinya selalu berada di sisinya apa pun yang terjadi, tetap setia menantinya kembali sebrengsek apa pun dirinya. Namun saat dia menyadari hal tersebut, semua sudah terlambat, istrinya terkena stroke. Hilang sudah segala kemampuannya untuk menyenangkan suaminya. Seandainya dulu, biaya pengobatan ini pasti terlihat murah untuknya, tetapi bahkan sekarang rumah pun mereka sudah tidak punya, sudah disita untuk membayar hutang-hutangnya. Tak dapat lelaki ini memaafkan dirinya, tidak melihat cinta yang begitu besar dari istrinya. Hilang sudah sayang dari anak-anaknya, tetapi tidak dengan cinta dari istrinya. Namun saat ia menyadarinya, semua sudah terlambat baginya untuk balas mencintai istrinya. Mungkin itulah hukuman dari Tuhan untuknya yang sempat berpaling ke jalan yang gelap, dan hukuman ini tidak terkira sakitnya bagi lelaki ini. Cinta saja tidak cukup baginya untuk menebus segala dosa dan kesalahan pada istrinya. Namun istrinya menerimanya kembali, dengan cinta yang sama seperti dulu, dengan perasaan yang sangat tulus, ia memaafkan suaminya. Akhir dari cerita ini adalah seperti yang kau lihat saat ini, Nak…” Akhirnya kakek itu menamatkan ceritanya. Tak terasa sebulir air mata mengalir turun di wajahku. Sakit rasanya dadaku mendengar cerita sang kakek.
Susah payah aku menahan tangis dan menelan air ludah, “lalu, apa yang akan Kakek lakukan sekarang? Ada apa dengan nenek?” Aku kembali mengulangi pertanyaanku di awal tadi. Sekali lagi sang kakek hanya tersenyum.
“Nenek sekarang sudah tenang, Nak, dia sudah selesai memberikan hadiahnya untukku. Walaupun tugasku untuknya masih belum selesai, masih banyak hutang yang harus kubayarkan kepadanya, tetapi untuk tugas terakhirku sekarang adalah membawanya ke tempat tidurnya yang terakhir dan terbaik.” Hanya itu jawaban sang kakek. Tangannya yang keriput kemudian mulai menarik gerobak tuanya. Tubuh sang nenek yang sudah kaku, terlihat meringkuk dalam gerobak tersebut. “Selamat tinggal, Nak! Hidup ini adalah sebuah anugerah terindah!” Pesan sang kakek seraya melambaikan tangannya padaku.
Langit sore ini mendung, tetapi matahari bersinar cerah, membuat suasana sore yang berwarna jingga ini menjadi sendu. Satu cerita itu sudah membuka mataku. Setiap hal kecil yang kita miliki adalah sebuah anugerah. Aku bodoh karena sudah meremehkan hidupku. Menjalani hidup bagai robot atau menikmati setiap momennya, itu merupakan pilihan sendiri, dan aku bodoh karena sudah memilih untuk menjadi
robot dan mengutuk hidupku.
Pertemuan dengan pasangan kakek-nenek itu sudah mengubah hidupku. Sekarang setiap momen adalah suatu harta tersendiri yang tidak akan pernah terulang lagi bagiku. Sekarang aku memandang segalanya berbeda. Sebuah cerita yang singkat, tetapi rumit dan penuh lika-liku, aku mengucapkan banyak terima kasih kepada sang kakek karena telah mengubah hidupku menjadi lebih berarti berkat ceritanya. Namun saat selesai bercerita, saat itulah terakhir kali aku bertemu dengannya…